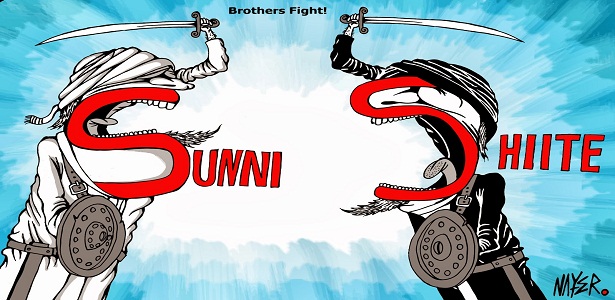Latar Belakang
Secara prinsipil perbuatan moral dalam pola pikir orang Islam tak bisa dipisahkan dengan pandangan agama, unsur teologi bernuansa religius. Hal itulah yang menjadi karakteristik khas dari filsafat Islam sejak semula. Inti pemikiran Islam yang diajarkan adalah Allah yang Esa dan sosok Nabi Muhammad sebagai teladan hidup sempurna bagi manusia (insan al’kamil).
[1]
Dalam pandangan filsafat, etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral, etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga hipotesis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang di anggap sebagai nilai relatif. Etika ingin menjawab pertanyaan “Bagaimana hidup yang baik?” Jadi etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak kepada kebijakan. Para filosof Yunani kuno membedakan pengetahuan (knowledge) dari hikmah (wisdom), di mana pengetahuan itu dipahami untuk kemudian menjadi sesuatu yang dapat diajarkan. Pengetahuan itu penting dan dibutuhkan untuk memperoleh hikmah. Tetapi tidak dengan sendirinya pengetahuan akan menjamin hadirnya kebijaksanaan, unsur-unsur lain yang dibutuhkan selain pengetahuan adalah pemahaman, wawasan, penilaian yang baik dan mengasah kemampuan untuk hidup dengan baik dan perilaku baik.
Banyak orang berpendidikan, pada kenyataannya, tidak layak dalam membuat keputusan praktis dalam kehidupan mereka dan mereka tidak terasa lebih baik secara moral dalam menjalani kehidupan. Mereka memiliki pengetahuan, tetapi kurang kebijaksanaan. Melalui filsafat moral, orang diharapkan akan senantiasa cinta dan mengejar kebijaksanaan dalam hal moral. Ilmu pengetahuan telah merangsang manusia untuk berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Daya berpikir inilah yang memampukan manusia menemukan disiplin ilmu baru: manusia tidak hanya stagnan pada keberhasilan-keberhasilan para pendahulunya. Namun, ketika manusia mampu mencipta dan daya berpikirnya semakin canggih, manusia kadangkala jatuh ke lembah kesombongan, saat itulah nilai-nilai moral dan norma-norma tradisional semakin merosot.
Membahas ihwal etika, tak bisa dipungkiri bahwa kedudukannya sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya etika, kehidupan manusia akan lebih terarah karena adanya suatu hukum yang mengatur dan menjelaskan ketentuan mana yang baik dan yang buruk. Namun, dalam praktiknya, dasar atau teori penggunaan etika yang dianut oleh tiap manusia berbeda-beda. Dalam hal ini, kita sebut saja etika barat yang cenderung menggunakan teori antroposentris dalam penerapan etikanya, sementara di etika Islam menggunakan teori theosentris.
Etika teologis yang dipakai oleh etika Islam tak terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran dan pandangan ahli pikir Islam, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah seorang teolog yang memberikan sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua hal. Dalam membahas etika, beliau juga menyumbangkan pemikirannya yang luar biasa, salah satunya lewat karyanya Ihya’ Ulum Al-Din yang sangat terkenal. Pemikirannya ini sampai saat ini digunakan sebagai rujukan bagi banyak orang untuk beretika dengan baik.
A. Riwayat Hidup Al-Ghazali
Beliau bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Namanya kadang diucapkan Ghazzali (dua z) artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan ayah Al-Ghazali adalah tukang pintal benang. Sedangkan yang lazim adalah Ghazali (satu z), diambil dari kata Ghazalah, nama kampung halamannya.
[2] Beliau lahir pada tahun 450 H/ 1058 M di desa Thus, wilayah Khurasan, Iran,dan meninggal di Thus pada
1111 M / 14 Jumadil Akhir 505 H dengan umur 52–53 tahun.
Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, filosof dan teolog muslim Persia yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Beliau adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar “Pembela Islam” (Hujjatul Islam), “Hiasan Agama” (Zainuddin), “Samudra yang Menghanyutkan” (Bahrun Mughriq), dan lain-lain.
[3] Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad.
Masa muda Al-Ghazali bertepatan dengan bermunculannya para cendekiawan, baik dari kalangan bawah, menengah, sampai elit. Kehidupan saat itu menunjukkan kemakmuran tanah airnya, keadilan para pemimpinnya, dan kebenaran para ulamanya. Sarana kehidupan kala itu sangat mudah didapat, masalah pendidikan sangat diperhatikan, pendidikan dan biaya hidup para penuntut ilmu ditanggung oleh pemerintah dan pemuka masyarakat.
[4]
Walaupun ayah Al-Ghazali seorang buta huruf dan miskin, beliau amat memeperhatikan asalah pendidikan anak-anakanya. Sesaat sebelum meninggal, ia berwasiat kepada salah seorang sahabatnya yang sufi agar memeberikan pendidikan kepada kedua anaknya, Ahmad dan Al-Ghazali.
Kesempatan emas ini dimanfaatan oleh al-Ghazali untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Mula-mula beliau belajar agama sebagai pendidikan dasar pada seorang ustad setempat, Ahmad bin Muhammad Razkafi. Kemudian beliau pergi ke Jurjan dan menjadi santri Abu Nasr Ismaili.
Setelah menamatkan studi di Thus dan Jurjan, Al-Ghazali melanjutkan dan meningkatkan pendidikannya di Naisabur dan bermukim di sana. Tak berapa lama kemudian, mulailah beliau mengaji kepada al-Juwain Imam Al Haramain hingga meninggalnya terakhir pada 478 H/1085 M. Beberapa lain disebutkan, tapi kebanyakan tidak jelas. Yang jelas adalah Abu ‘Ali Al Farmadhi. Dari Naisabur pada 478 H/1085 M, beliau pergi ke kampus Nizam Al Mulk yang menarik banyak sarjana. Di sana beliau diterima dengan kehormatan dan kemuliaan. Sebelum perpindahannya ke Bagdad, Al Ghazali mengalami fase skeptisisme, dan menimbulkan awal pencarian yang penuh semangat terhadap sikap intelektual yang lebih memuaskan dan cara hidup yang lebih berguna.
[5]
Pada 484 H/ 1091 H, Al Ghazali diutus oleh Nizam Al Mulk manjadi guru besar di Madrasah Nizhamiyyah yang didirikan di Bagdad. Beliau menjadi salah satu dari orang yang paling terkenal di Bagdad, dan selama empat tahun memberikan kuliah pada peserta yang jumlahnya mencapai lebih dari tiga ratus mahasiswa. Pada saat yang sama, beliau menekuni kajian filsafat lewat bacaan pribadi dan menulis sejumlah buku. Namun, pada 488 H/ 1095 M beliau menderita penyakit jiwa yang membuatnya secara fisik tak dapat lagi member kuliah. Motif-motif pengunduran diri Al Ghazali masih didiskusikan sampai saat ini. Alasan yang beliau berikan adalah untuk melaksanakan ibadah haji, namun ada yang mengatakan bahwa beliau ingin meninggalkan status guru besar dan kariernya secara keseluruhan sebagai ahli hukum dan teolog.
Sejak kepergiannya dari Bagdad, Al Ghazali telah menghabiskan waktu sekitar sepuluh sampai sebelas tahun untuk mengembara. Beliau menghabiskan beberapa waktu di Damaskus, lalu pergi ke Madinah dan Makkah lewat Jerussalem dan Hebron sambil melaksanakan haji pada 489 H/ November-Desember 1096 M. Kemudian beliau kembali ke Damaskus dan pernah pula dilaporkan terlihat di Bagdad pada bulan Jumada Al-Tsaniyah 490 H/ Mei-Juni 1097 M, tetapi ini mungkin hanya singgah sejenak dalam rangkaian perjalanan ke kampung halamannya, Thus.
[6]
Pada periode pengunduran dirinya di Damaskus dan Thus, Al Ghazali hidup sebagai sufi yang miskin, selalu menyendiri, menghabiskan waktunya dengan meditasi dan pelatihan ruhaniah-ruhaniah lainnya. Pada periode inilah beliau menulis Ihya Ulum Al-Din, karya besarnya tentang etika. Pada 499 H/ 1105-6 M, Fakr Al-Mulk, putra Nizam Al-Mulk, dan wazir Sanjar, penguasa Saljukiah di Khurasan, menekan Al Ghazali untuk kembali ke kerja akademik. Beliau menyerah atas penekanan ini, sebagian di dorong oleh kepercayaan bahwa beliau ditakdirkan untuk menjadi pembantu agama (mujaddid). Pada bulan Dzulqadah/ Juli-Agustus 1106 M, al Ghazali mulai mengajar di Nizamiyah di Nasyabur dan tidak lama setelah itu menulis autobiografis Al-Munqidz min Al-Dhalal. Namun, sebelum meninggal beliau berhenti kembali mengajar dan kembali ke Thus.
[7]
B. Karya-karya Al-Ghazali
Al-ghazali adalah seorang ulama dan ahli pikir Islam yang memiliki ketinggian ilmu. Beliau mempuni di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Banyak karya yang diciptakannya melalui pengetahuannya yang luas itu.
Karangan al-Gazali berjumlah kurang lebih dari 100 buah. Karangan-karangannya mengikuti berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan., seperti ilmu kalam (teologi Islam), Fiqh (hukum Islam, Tasawuf, akhlak dan autobiografi. Sebagian besar dari karangannya adalah berbahasa arab dan sebagian lagi berbahasa persia.
Di antara berbagai karya itu ada beberapa yang kurang mendapat perhatian di kalangan ulama Indonesia. Namun sangat dikenal oleh negeri barat. Yaitu di antaranya buku yang menyebabkan polemik di antara ahli filsafat, buku tersebut adalah Maqasidul Falasifah (tujuan para ahli filsafat) dan Tahafut al-Falasifah (kesesatan kaum filosof). Buku yang terakhir ini dikenal sebagai kitab paling penting untuk mengkritik pemikiran para filosof. Sebagamana dicatat Miska Muhammad Amin: “dalam bidang filsafat, karyanya yang sempat mengejutkan dunia kefilsafatan berjudul Tahafut al-Falasifah (kesesatan kaum filsuf). Dalam buku ini al-Gazali mengkritik beberapa kesalahan dan kesesatan para filsuf islam dimasa itu”
[8]
Kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam berpindah-pindah antara Syam, yerussalem, hijaz dan Yus dan berisi paduan indah antara fiqh, tasawuf dan falsafah, bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tapi juga di dunia barat.
[9] Masih banyak karya al-Gazali lainnya yang terkenal maupun yang tidak begitu populer. Dia meninggalkan sejumlah besar karya bagi kaum muslimin dan dunia pada umumnya.
Disiplin Ilmu
Karya
Tasawuf
a) Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
b) Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)
c) Misykah al-Anwar (The Niche of Lights)
Filsafat
a) Maqasid al-Falasifah
b) Tahafut al-Falasifah, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh
Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).
Fiqh
a) Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul
Logika
a) Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)
b) Al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)
c) Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)
[10]
Karya pertama Al-Ghazali yang membahas tentang etika adalah Maqashid Al-Falasifah. Buku ini ditulis ketika beliau sedang mengkaji filsafat pada waktu senggangnya selama periode kurang dari dua tahun, yaitu setelah tahun 484 H/ 1091-2 H dan sebelum tahun 486 M/ 1094 M. Pernyataan pertama Al-Ghazali mengenai etika terungkap di dalam sebuah konteks yang member kesan bahwa etika itu dipungut dari para filosof. Pernyataan yang lebih personal dan positif ditemukan dalam dua karya yang lain, yag secara kronologis diikuti satu sama lain, yaitu Mi’yar Al-‘Ilm dan Mizan Al-‘Amal.
[11]
Karya Al-Ghazali yang terpenting mengenai etika adalah Ihya’ Ulum Ad-Din, terutama jilid III dan IV. Mizan Al-‘Amal dan Ihya’ Ulum Ad-Din adalah dua risalah Al-Ghazali yang membahas teorietika secara terperinci. Bedanya adalah karya yang terdahulu merupakan ringkasan dari karya yang belakangan. Kemudian, Al-Ghazali membahas masalah universalitas norma etika ditulis dalam Al-Mustasyfamin Al-Ushul. Beliau juga menjelaskan secara panjang lebar makna etika normative mengenai baik dan buruk dalam karya ini.
[12]
C. Pemikiran Al-Ghazali tentang Etika
Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan sufisme dengan syariah, yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah bagian dari efek atas ketertarikannya terhadap sufisme sejak berusia masih belia. Ia juga tercatat sebagai sufi pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya.
[13]
Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Asy’ariyah yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam. Gagasan etikanya dibangun melalui perhubungan paradigm wahyu dengan tindakan moral, stressingnya bahwa kebahagiaan adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Keutamaan-keutmaan merupakan pertolongan Tuhan yang niscaya sifatnya terhadap jiwa. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan, usaha mandiri manusia dalam mencari keutamaan akan sia-sia dan bahkan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.
[14]
Penegasan tersebut membuktikan bahwa al-Ghazali bermaksud menyamakan pengertian etika atau moralitas sama halanya dalam teologi Islam yang jatuh pada reduksionisme teologis. Artinya al-Ghazali menempatkan wahyu al-Quran menjadi petunjuk utama atau bahkan satu-satunya dalam tindakan etis, dan dengan keras menghindari intervensi rasio dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar universal tentang petunjuk ajaran al-Quran bagi kehidupan manusia (etika mistis lawan etika rasional spekulatif).
[15]
Perdebatan teologi juga berimplikasi pada perdebatan tentang etika dalam Islam. Sebagian besar kontroversi bidang etika dalam filsafat Islam adalah bersumber dari perdebatan-perdebatan teologi yang paling pokok. Perdebatan antara kelompok Asy’ariyah dan Mu’tazilah adalah salah satu contoh yang pernah menghiasi sejarah pemikiran Islam.
Menurut kalangan Asy’ariyah, makna etika murni bersifat subyektif, bisa mempunyai makna apabila ada subyek (Allah). Satu-satunya tujuan bertindak moral adalah untuk mematuhi Allah. Bagi mereka, makna moralitas hanya bisa dipahami apabila mampu bertindak selaras dengan kehendak dan perintah Allah. Sedangkan kalangan Mu’tazilah berpendapat bahwa semua perintah Allah benar adanya, dan sifat benarnya terpisah dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan-landasan obyektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak dapat menunut kita untuk melakukan sesuatu yang benar karena aturan-aturan moralitas bukanlah ha-hal yang berada di bawah kendali-Nya.
Perdebatan dua madzhab tersebut masih berlanjut hingga kini. Kalangan Asy’ariyah memandang moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Akantetapi, kalangan Mu’tazilah berpandangan sebaliknya. Mereka memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama.
Salah satu tokoh Asy’ariyah yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam adalah al-Ghazali. Beliau menghubungkan wahyu dengan tindakan moral. Al-Ghazali menyarankan kepada kita untuk memandang kebahagiaan sebagai pemberian anugerah Tuhan. Al-Ghazali menganggap keutamaan-keutamaan dengan pertolongan Tuhan adalah sebuah keniscayaan dalam keutamaan jiwa. Jadi, dengan menerapkan istilah keutamaan kepada pertolongan Tuhan, Al-Ghazali bermaksud menghubungkan keutamaan dengan Tuhan. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.
[16]
Rupanya, al-Ghazali ingin menyamakan pengertian etika atau moralitas sama halnya dalam teologi Islam. Menurut Amin Abdullah, al-Ghazali jatuh pada “reduksionisme teologis”. Artinya, al-Ghazali menempatkan wahyu al-Qur’an menjadi petunjuk utama --atau bahkan satu-satunya-- dalam tindakan etis, dan dengan keras menghindari intervensi rasio dalam merumuskan prinsip-prinsip dasar universal tentang petunjuk ajaran al-Qur’an bagi kehidupan manusia. Titik perbedaan antara filsafat etika al-Ghazali dan Kant terletak pada penggunaan rasionalitas. Al-Ghazali menyusun teori etika mistik, sedang Kant membangun sistem etika rasional yang teliti untuk menggantikan doktrin metafisika-dogmatik-spekulatif.
[17]
Menurut al-Ghazâlî akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan di mana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang berakhlak baik, ketika menjumpai orang lain yang perlu ditolong maka ia secara spontan menolongnya tanpa sempat memikirkan resiko. Demikian juga orang yang berakhlak buruk secara spontan melakukan kejahatan begitu peluang terbuka.
[18]
Etika atau akhlak menurut pandangan al-Ghazali bukanlah pengetahuan (ma’rifah) tentang baik dan jahat atau kemauan (qudrah) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (fi’il) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibn Miskawaih bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan-kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun al-Ghazali membaginya ke dalam tiga; daya nafsu, daya berani, dan daya berfikir, sama dengan Ibn Miskawaih.
[19] Menurut al-Ghazali watak manusia pada dasarnya ada dalam keadaan seimbang dan yang memperburuk itu adalah lingkungan dan pendidikan. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu tercantum dalam syariah dan pengetahuan akhlak. Tentang teori Jalan Tengah Ibn Miskawaih, al-Ghazali menyamakannya dengan konsep Jalan Lurus (al-Shirât al-Mustaqîm) yang disebut dalam al-Qur’an dan dinyatakan lebih halus dari pada sehelai rambut dan lebih tajan dari pada mata pisau. Untuk mencapai ini manusia harus memohon petunjuk Allah karena tanpa petunjuk-Nya tak seorang pun yang mampu melawan keburukan dan kejahatan dalam hidup ini.
[20]
Al-Ghazali untuk pertama kalinya menghancurkan otoritas Aristoteles dan pada saat yang sama menabur bibit-bitit filsafat mekanika, fondasi metafisika untuk sains modern. Maka kontribusinya itu tidak hanya deskruktif, tetapi juga konstruktif. Alih-alih menghambat perkembangan sains, al-Ghazali adalah seorang agen dalam memfasilitasi kemajuan yang lebih jauh. Sebagai seorang individu ia telah mencapai untuk pertama kalinya antara tahun 1094 dan 1108 hal-hal yang sama seperti apa dicapai orang-orang eropa selama lima abad 12 hingga abad 17.
Dengan demikian al-Ghazali mensimbolisasikan individualisme (suatu pemikiran yang bernilai pada zaman renaisans) dalam cara yang paling baik, dan menyerang atau menghancurkan ide-ide bid’ah Aristoteles dan paham Aristotelianisme dalam tiga tahun, yaitu tahun 1092 hingga 1095. Perlu dicatat bahwa Al-Ghazali berbicara pada tataran tinjauan teologi Islam sementara kebanyak pemikir etika barat sedikit banyaknya mengambil manfaat dari ide-ide al-Ghazali.
[21]
Selain itu berdsarkan pandangan teologis al-Ghazali menolak pandangan kausalitas dalam tindakan etis. Dia tidak dapat membenarkan hubungan kausal antara sanksi dan pahala karena tidak bersifat rasional. Dari pemahaman dasar ini dia menyatakan bahwa kebaikan dan kejahatan hanya dapat diketahui melalui wahyu dan menolak bahwa perintah-perintah Tuhan dalam al-Quran memiliki tujuan tertentu. Akhlak seseorang, disamping bermodal pembawaan sejak lahir, dia juga dibentuk oleh lingkungan dan perjalanan hidupnya. Nilai-nilai akhlak Islam yang universal bersumber dari wahyu, disebut al-khayr, sementara nilai akhlak rasional bersumber dari budaya setempat disebut al-ma’ruf, atau sesuatu yang diketahui masyarakat sebagai kebaikan dan kepatuhan.
[22]
Sedangkan aklhak yang bersifat lahir disebut adab, tatakrama, sopan santun atau etika. Selain itu juga terdapat aklha universal yang berlaku untuk seluruh manusia sepanjang zaman, dan hal tersebut berjalan sesuai dengan keragaman manusia. Disisi lain, juga dikenal ada akhlak yang spesifik, misalnya akhlak anak kepada kepada orang tua dan sebaliknya, akhlak murid kepada guru dan sebaliknya, akhlak pemimpin kepada yang dipimpin dan sebagainya.
[23]
Seorang dapat menjadi pemimpin dari orang banyak manakala ia memiliki tiga kriteria berikut:
1. Memiliki kelebihan disbanding yang lain, sehingga dengan kelebihan tersebut ia bisa memberi.
2. Memiliki keberanian dalam memutuskan sesuatu, dan
3. Memiliki kejelian dalam memandang masalah sehingga ia bisa bertindak arif dan bijaksana.
[24]
Menurut etika keagamaan, seorang pemimpin pada hakekatnya adalah pelayan dari orang banyak yang dipimpinnya. Pemimpin yang akhlaknya rendah pada umumnya lebih menekankan dirinya sebagai penguasa, sementara pemimpin yang berakhlak baik lebih menekankan dirinya sebagai pelayan masyarakat.
Dampak dari keputusan pemimpin akan sangat besar implikasinya pada rakyat yang dipimpin. Jika keputusannya tepat, maka kebaikan akan meratakepada rakyatnya, tetapi jika keliru maka rakyat banyak akan menanggung derita karenanya. Oleh karena itu pemimpin yang baik disebut oleh Nabi dengan pemimpin yang baik (Imanum Adil) sementara pemimpin yang buruk digambarkan dalam al-Quran dan juga al-Hadist sebagai pemimpin yang salim (Imamum Zhalim). Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebaliknya pemimpin salim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Kisah dalam al-Quran yang menyebut Nabi Sulaiman yang memperhatikan suara semut mengandung pelajaran bahwa betapapun seseorang menjadi pemimpin besar, tetapi ia tidak boleh melupakan rakyat kecil yang dimisalkan semut itu.
[25] Meneladani kepemimpinan Rasulullah saw. meniscayakan keteladanan yang baik terutama dalam kehidupan pribadi, seperti: hidup bersih, sederhana dan mengutamakan orang lain. Ini merupakan sebuah alasan mengantarkan Al-Ghazali dianggap sebagai seorang filsuf walaupun dia tidak suka disebut sebagai seorang filsuf.
Secara sosial pemimpin adalah penguasa, karena ia memiliki otoritas dalam memutuskan sesuatu yang mengikat orang banyak yang dipimpinnya.
[26] Secara sosial etika Islam memiliki peran yang sangat besar bagi perbaikan atas kehidupan umat manusia. Etika sosial Islam mempunyai dua ciri yang sangat mendasar, yaitu keadilan dan kebebasan. Dua ciri ini penting untuk menggerakkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Perbuatan kita mesti diorientasikan pada tindakan-tindakan yang mengarah pada keadilan dan juga memandang kebebasan mutlak setiap individu. Karena, kebebasan individu ini berimplikasi pada tindakan sosial dan syariat kolektif.
Sudah semestinya, etika Islam tidak hanya dimaknai sebagai etika individual saja, tapi juga perlu dipahami sebagai ajaran sosial. Kehidupan umat manusia perlu dibangun dengan perspektif agama yang lebih memperdulikan pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan. Jadi, Islam tidak semata diartikan sebagai ritualisasi ibadah dan etika individual semata, tapi juga sebagai agama yang penting untuk memperbaiki kehidupan sosial secara lebih luas.
Dalam kitabnya Ihya’ Ulum Al-Din, Imam Al-Ghazali mengungkapkan pandangan etikanya antara lain:
- Akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang baik sebagaimana perangai ulama, syuhada’, shiddiqin, dan Nabi-nabi. Oleh karenanya, Al-Ghazali mengedepankan konsep tashfiyat al-nafs(penjernihan jiwa) sebagai proses pembersihan hati dari berbagai sifat yangmadzmumah, dan takmil al-nafs (penyempurnaan jiwa) dengan berbagai sifat yang mahmudah.[27]
- Akhlak yang baik dapat mengadakan perimbangan antara tiga kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berfikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Akhlak yang baik acapkali menentang apa yang digemari manusia.
- Akhlak itu adalah kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia yang secara mudah dan tanpa perlu berpikir menumbuhkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan terpuji, maka dinamakan akhlak baik, dan apabila yang lahir itu tingkah laku yang keji, dinamakanlah akhlak yang buruk.[28]
d. Tingkah laku seseorang itu adalah lukisan batinnya.
e. Berbicara tentang “kebiasaan”, Al-Ghazali mengemukakan bahwa kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima suatu pembentukan, tetapi lebih condong kepada kebajikan dibanding dengan kejahatan. Jika kemudian diri manusia membiasakan yang jahat, maka menjadi jahatlah kelakuannya. Demikian juga sebaliknya, jika membiasakan kebaikan maka baiklah tingkah lakunya.
f. Berbicara tentang pentingnya latihan dan pendidikan akhlak, al-Ghazali mengutarakan bahwa jiwa itu dapat dilatih, dikuasai dan diubah kepada akhlak yang mulia dan terpuji. Tiap sifat tumbuh dari hati manusia dan memancarkan akibatnya kepada anggotnya. Seseorang yang ingin menulis bagus, pada mulanya harus memaksakan tangannya menulis bagus. Apabila kebiasaan itu sudah lama, maka paksaan itu tidak diperlukan lagi karena digerakkan oleh jiwa dan hatinya.
[29]
g. al-Ghazali menempatkan kebahagiaan jiwa manusia sebagai tujuan akhir dan kesempurnaan dari akhlak. Kebahagiaan tertinggi dari jiwa berarti mengenal adanya Allah tanpa keraguan (ma’rifatullah).
[30]
Kesimpulan
Berpijak dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka pada bagaian penutup ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
- Etika Islam tidak bisa terlepas dari salah satu ahli pikir Islam termasyhur, Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki semangat untuk belajar tinggi meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Semangat belajar inilah yang menghantarkannya memliki keilmuan tinggi yang bermanfaat bagi umat manusia sampai sekarang ini. Lantaran semangat belajar ini pula, beliau mampu menguasai berbagai disiplin ilm pengetahuan dan menyumbangkan emikirannya di setiap disiplin ilmu tersebut.
- Kehebatan Al-Ghazali dapat diketahui melalui pembuktian yang diusungnya lahirnya gagasan orisinil melalui beberapa kitab karangannya sendiri.
- Dalam membahas etika, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum Al-Din menerangkan bahwa akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dari sifat-sifat buruk kepada sifat-sifat baik. Akhlak tersebut didorong oleh kekuatan pikir, hawa nafsu, dan amarah dimana akhlak yang baik dapat menyeimbangkan ketiga hal tersebut. Tingkah laku manusia menggambarankan keadaan batin manusia tersebut. Tingkah laku yang buruk dapat diubah dengan latihan dan pendidikan akhlak agar mampu mencapai akhlak yang mulia dan terpuji. Dan yang tak kalah penting adalah membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, sehingga akan menjadi baik pula tingkah lakunya. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat al-Ghzali mengusung pemikiran etikanya berlandaskan al-Quran dan sunnah, sedangkan akal atau rasionalitas menurut al-Ghazali hanya dipandang sebagai instrument argumentatif turunan dari kedua asas tersbut.
B. Implikasi
Dalam pandangan filsafat, etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral, etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga hipotesis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang di anggap sebagai nilai relatif. Jadi etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak kepada kebijakan. Berangkat dari moral yang mendorong seseorang melakukan perbuatan yang baik, etika adalah sebuah rambu-rambu didalam bertindak yang akan membimbing dan mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagaman pemikiran etika al-Ghazali yang berorientasi lebih pada penyelamatan individu di akhirat berdasarkan doktrin agama. Dan karena penilaiannya rendah terhadap rasio dalam wacana etika, metode al-Ghazali hanya sedikit membuka ruang bagi pengetahuan dalam wilayah wilayah lain dalam kehidupan manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Hadziq, M.A., Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik, Semarang: RaSAIL, 2005
Amin M. Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, Bandung: Mizan, 2002.
Barsihannor Etika Islam Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Bertens K., Etika Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
Darul Dida Ulum, Filsafat Etika antara Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali dalam Barsihannor Etika Islam Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
al-Ghazāli. Ihyâ’ ‘ulûm al-dîn, vol 10. (Revival of the Religious Sciences). Terj. Sabih Ahmad Kamali, Cairo: Mu’assasat al-Halabî wa-Shurakâ’hu, 1968.
Hidayat Komaruddin, Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
Ibnu Abidin Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Mahjuddin, Kuliah Akhlak-Tasawuf Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
Muhammad Miska Amin, Epistemologi Islam Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam, Jakarta: UIP, 1984.
Mustafa, Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah dan Ushuluddin Komponen Mkdk, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
Mondin Battista, A History of Mediaeval Philosophy Roma: Urbaniana University Press, 1991.
Ohoitimur Johanis, Sejarah Filsafat Abad Pertengahan, Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng, 2009
Putjowijatno, Etika, Filsafat, Tingkahlaku Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Quasem M. Abul dan Kamil. Etika Al-Ghazali: Etika Majemuk di dalam Islam. Terj. J. Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1988.
Ya’qub Hazah, Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar), Bandung: CV Diponegoro, 1988.
http: //www.wikipedia.com. disadur pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 10.23 wib.
[1]Battista Mondin. A History of Mediaeval Philosophy (Roma: Urbaniana University Press, 1991), h. 222.
[2]Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9.
[3]Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan. h. 9
[4]Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan. h. 9-10
[5]M. Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, (Bandung: Mizan, 2002), h. 28-29.
[6]M. Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, h. 29-30.
[7]M. Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, h. 30-31.
[8]Miska Muhammad Amin Epistemologi Islam Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam (Jakarta: UIP, 1984). h. 49
[9]Mustafa Filsafat Islam Untuk Fakultas Tarbiyah, Syariah, Dakwah Dan Ushuluddin Komponen Mkdk (bandung; pustaka setia, 1999), h.220
[10]http: //www.wikipedia.com. disadur pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 10.23 wib.
[11]M. Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, h. 32.
[12]M. Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, h. 32.
[13]Dida Darul Ulum, Filsafat Etika antara Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali dalam Barsihannor Etika Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 236
[14]K. Bertens, Etika (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 13
[15] Amin Abdullah, Antara Al Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam, h. 11
[16]K. Bertens, Etika dalam Barsihannor Etika Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 236
[17]Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam: Antara al-Ghazali dan Kant, h. 11
[18]Komaruddin Hidayat, Kontekstualisasi Islam dalam Sejarah (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 22.
[19]Barsihannor Etika Islam, h.237
[21]Barsihannor Etika Islam, h.238
[22]Mahjuddin, Kuliah Akhlak-Tasawuf (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 21
[23]Barsihannor, Etika Islam, h. 239.
[24]Putjowijatno, Etika, Filsafat, Tingkahlaku (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 35.
[26]Pudjowijatno, Etika, Filsafat Tingkah Laku, h. 35.
[27]H. Abdullah Hadziq, M.A., Rekonsiliasi Psikologi Sufistik dan Humanistik, (Semarang: RaSAIL, 2005), h. 216-217.
[28]al-Ghazāli. Ihyâ’ ‘ulûm al-dîn, vol 10. (Revival of the Religious Sciences). Terj. Sabih Ahmad Kamali. (Cairo: Mu’assasat al-Halabî wa-Shurakâ’hu, 1968), h. 96. Lihat juga M. Abul Quasem dan Kamil. Etika Al-Ghazali: Etika Majemuk di dalam Islam, terj. J. Mahyudin. (Bandung: Pustaka, 1988), h. 81-82.
[29]H. Hazah Ya’qub, Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar), (Bandung: CV Diponegoro, 1988), h. 91-92.
[30]Johanis Ohoitimur, Sejarah Filsafat Abad Pertengahan” (Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng, 2009), h. 98.